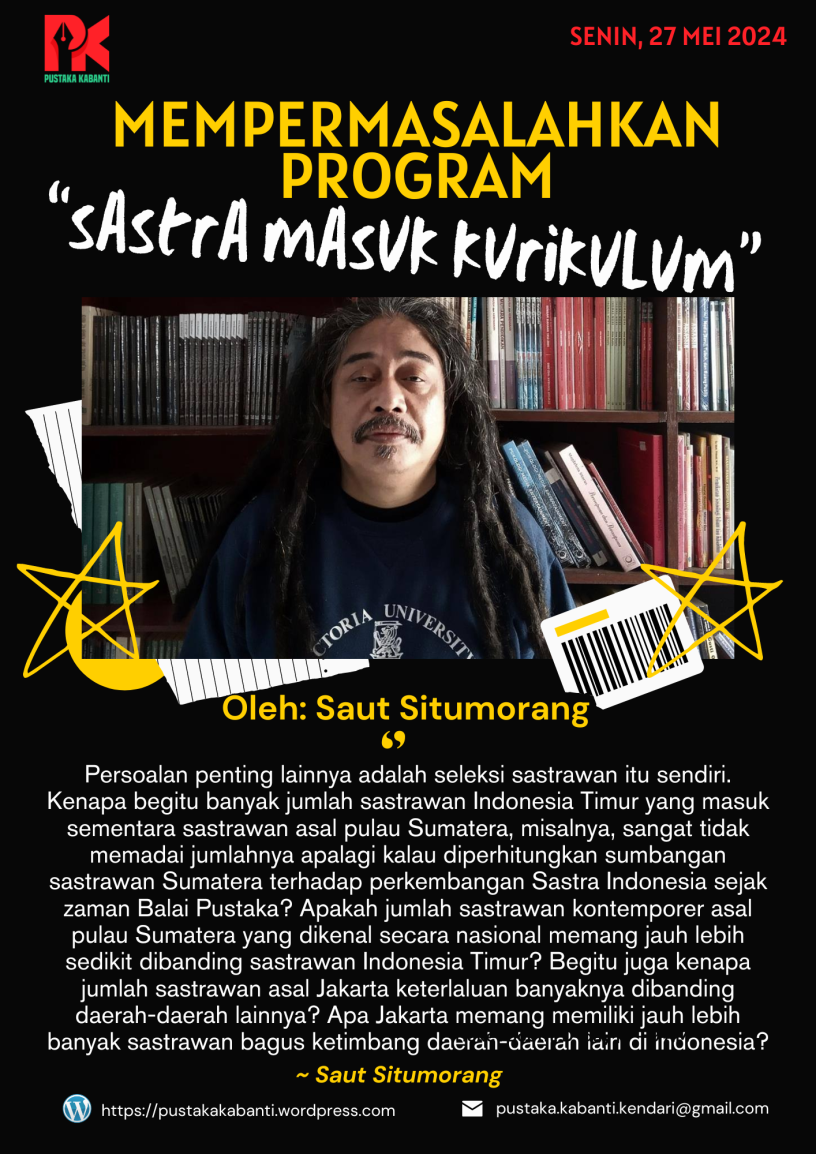Oleh: Saut Situmorang
“tahun 2020 buku puisi saya “lelaki dan tangkai sapu” mendapatkan penghargaan sastra dari badan bahasa kemendikbud RI. waktu itu jurinya Abdul Hadi WM, Eka Budianta, Joko Pinurbo. tahun 2019 buku puisi saya yang berjudul “mencari jalan mendaki” dapat penghargsan dari Perpusnas RI. jurinya Maman S. Mahayana dkk. tapi ketika ada program sastra masuk kurikulum buku tersebut tidak direkomendasikan. apakah juri atau penghargaan tersebut tidak diakui? salam puisi tak henti-henti…i”, demikian tulis penyair Payakumbuh Iyut Fitra dalam status Facebooknya, Selasa 21 Mei 2024.
Pertanyaan Iyut Fitra di atas valid dalam konteks peluncuran program “Sastra Masuk Kurikulum” oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada Senin 20 Mei 2024. Ada 177 buku yang direkomendasikan Kemdikbud untuk dibaca anak-anak sekolah mulai dari Jenjang SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA/MAK dan tak satu pun buku Iyut Fitra masuk dalam rekomendasi tersebut.
Dalam Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra yang dikeluarkan Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bagian dari peluncuran program “Sastra Masuk Kurikulum” tersebut, disebutkan bahwa “Untuk memastikan standar mutu karya-karya [yang dipilih] tersebut, tim kurator juga menimbang berdasarkan penghargaan yang telah diperoleh, apakah karya tersebut telah diterjemahkan ke bahasa asing, dialihwahanakan, hingga dibahas dalam resensi-resensi di media yang memiliki kredibilitas ataupun menjadi subjek kajian akademis berupa skripsi, tesis, atau disertasi” sebagai bagian dari “kriteria kurasi”.
Berdasarkan “kriteria kurasi” di ataslah maka pertanyaan Iyut Fitra tadi valid dan sangat pantas, kalau tidak mau dikatakan penting, untuk diajukan. Kenapa kedua buku puisi Iyut Fitra yang merupakan pemenang penghargaan sastra dari dua lembaga negara itu tidak dimasukkan oleh Tim Kurator? Apakah memang, seperti yang dengan telak dinyatakan Iyut, “juri atau penghargaan tersebut tidak diakui?” oleh Tim Kurator? Kalau memang tidak diakui, apa alasannya?
Banyak persoalan memang dimiliki oleh program “Sastra Masuk Kurikulum” tersebut, disamping soal “penghargaan sastra” yang disebutkan Iyut Fitra di atas. Salah satu persoalan mendasar adalah tentang definisi dari istilah “sastra” yang dipakai sebagai nama dari program.
Tidak ada definisi istilah “sastra” yang diberikan walaupun istilah tersebut sangat royal diobral dalam kedua penerbitan program yang mengiringi peluncuran program “Sastra Masuk Kurikulum” yaitu Salinan Kepmen 025.H.P.2024 Rekomendasi Buku Sastra dan Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra yang disebar ke publik.
Dalam Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra dikatakan bahwa “karya sastra adalah media pembelajaran yang sangat potensial. Karya sastra mengundang pembaca untuk menghayati dunia batin tokoh-tokoh yang melihat dan mengalami sesuatu dengan caranya masing-masing. Karya-karya sastra terbaik juga mengupas isu-isu kompleks dan menyajikan perdebatan moral yang mendorong pembaca keluar dari pemikiran hitam-putih dan memikirkan ulang opini serta prasangka-prasangka yang mungkin tak disadari sebelumnya”.
Terlihat betapa fungsi karya sastra yang dijadikan alasan kenapa program “Sastra Masuk Kurikulum” dirancang dan diluncurkan. Apa “sastra” itu dan kenapa sebuah karya tulis dimasukkan dalam kategori “sastra” tidak ada disebutkan sama sekali.
Karena absennya definisi istilah “sastra” ini maka terjadilah kebebasan yang sangat kelewatan dalam seleksi karya-karya yang masuk dalam program “Sastra Masuk Kurikulum” tersebut. Akibatnya juga terjadi pemilihan asal-asalan atas karya seseorang yang dianggap sastrawan dalam sejarah Sastra Indonesia yaitu memilih karyanya yang sebenarnya tidak representatif terhadap identitasnya sebagai sastrawan!
Apakah novel-novel Laskar Pelangi, Balada Si Roy, dan Karmila itu, misalnya, memang karya sastra? Di mana “sastra”nya ketiga novel pop bestseller ini? Tidak ada penjelasan sama sekali dari Tim Kurator program “Sastra Masuk Kurikulum”.
Kemudian, apa alasannya untuk memilih Penyamun dalam Rimba dari keseluruhan korpus karya Mochtar Lubis yang dominan warna politiknya itu? Apakah Tim Kurator memang ingin agar para siswa SD mengenal Mochtar Lubis sebagai Pengarang Cerita Anak? Kembali tidak ada penjelasan sama sekali dari Tim Kurator program “Sastra Masuk Kurikulum”.
Persoalan penting lainnya adalah seleksi sastrawan itu sendiri. Kenapa begitu banyak jumlah sastrawan Indonesia Timur yang masuk sementara sastrawan asal pulau Sumatera, misalnya, sangat tidak memadai jumlahnya apalagi kalau diperhitungkan sumbangan sastrawan Sumatera terhadap perkembangan Sastra Indonesia sejak zaman Balai Pustaka? Apakah jumlah sastrawan kontemporer asal pulau Sumatera yang dikenal secara nasional memang jauh lebih sedikit dibanding sastrawan Indonesia Timur? Begitu juga kenapa jumlah sastrawan asal Jakarta keterlaluan banyaknya dibanding daerah-daerah lainnya? Apa Jakarta memang memiliki jauh lebih banyak sastrawan bagus ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia? Jumlah “sastrawan” muda yaitu mereka yang baru dikenal di era 2000an pun begitu banyak masuk dalam seleksi sampai sastrawan mapan seperti penyair Frans Nadjira dari Bali tidak dimasukkan sama sekali. Apa memang puisi Frans Nadjira tidak layak sama sekali untuk dipelajari siswa Indonesia dibanding “puisi” seorang Martin Suryajaya? Kembali Tim Kurator program “Sastra Masuk Kurikulum” membisu.
Tim Kurator juga gagal menjelaskan alasan mengapa jumlah novel begitu banyaknya yang masuk dibanding puisi dan cerita pendek. Apa menurut mereka novel itu lebih penting daripada puisi dan cerita pendek?
Persoalan-persoalan mendasar di atas bisa terjadi, saya sangat yakin, karena seleksi nama dan karya yang dilakukan tidak berdasarkan standar ilmu sastra (literary studies) yang sebenarnya. Bahkan konsep “sastra” yang dipakai pun tidak berasal dari konsep ilmu sastra. Sangat ironis memang padahal program pemerintah ini memakai istilah “sastra” di namanya dan “dirancang untuk membantu guru memanfaatkan karya sastra dalam pembelajaran Kurikulum Merdeka” seperti yang dinyatakan di Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.
Di atas saya katakan bahwa seleksi nama dan karya yang dilakukan tidak berdasarkan standar ilmu sastra (literary studies) yang sebenarnya dan bahkan konsep “sastra” yang dipakai pun tidak berasal dari konsep ilmu sastra. Pernyataan saya ini saya buat berdasarkan penilaian atas kacaunya pemahaman Tim Kurator atas arti dari konsep “sastra” itu sendiri yang terbukti dari dipilihnya para novelis pop yang tidak pernah dianggap sebagai sastrawan dalam studi sastra (literary criticism) yang sebenarnya seperti Andrea Hirata, Tere Liye, Gol A Gong, Eddy D. Iskandar dan Marga T. Itu juga alasannya kenapa Tim Kurator tidak (mampu) memberikan penjelasan kuratorial atas apa itu “sastra” atau minimal apa arti definisi istilah tersebut menurut mereka.
Akhir-akhir ini sebuah kajian teks bernama Kajian Budaya (Cultural Studies) telah mendominasi “Fakultas Ilmu Budaya” di seluruh Indonesia khususnya di jurusan Sastranya. Kajian Budaya yang tidak meyakini adanya Seni itu (yang membedakan sebuah teks dari teks yang bukan Seni), yang percaya bahwa semua teks adalah setara nilainya yaitu sebagai sekedar produk budaya an sich, jelas tidak mengakui keberadaan apa yang disebut sebagai Karya Sastra (literary work). Makanya bagi para penganut Cultural Studies, semua novel adalah novel dan karena Cultural Studies sudah memasuki dan mendominasi studi sastra di jurusan Sastra dari apa yang disebut sebagai Fakultas llmu Budaya (FIB) itu maka karena novel adalah salah satu genre dari Sastra maka semua novel adalah novel sastra. Titik. Tidak ada lagi pembicaraan tentang estetika atau faktor artistik yang selama ini kita kenal sebagai ciri pembeda karya sastra waktu membicarakan teks seperti novel misalnya.
Pandangan Cultural Studies itulah yang mendominasi seleksi nama dan karya dalam program “Sastra Masuk Kurikulum”. Makanya teks bergenre Travel Writing pun dianggap karya sastra dalam program kurikulum sekolah ini, Majalah Bobo pun dianggap karya sastra, dan komik pun dianggap karya sastra.
CATATAN: Pemuatan tulisan ini di Blog Pustaka Kabanti atas persetujuan penulisnya.